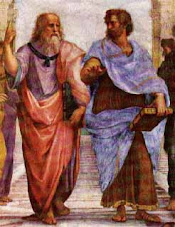Ikhtiar agar isi strategi pertanahan mampu
mengakomodasi kebutuhan petani, dan dapat diakui sebagai instrumen yang
memberdayakan petani, serta dapat dimaknai sesuai tujuannya oleh pihak-pihak
yang terkait langsung; akhirnya memunculkan relasi kuasa dalam memberdayakan
petani. Relasi kuasa (power relation)
adalah hubungan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya berdasarkan
ideologi tertentu. Kekuasaan (power)
adalah konsep yang kompleks dan abstrak, yang secara nyata mempengaruhi
kehidupan mereka. Kekuasaan didefinisikan sebagai kemampuan pemangku
kepentingan, untuk menentang atau mendukung individu atau kelompok lainnya
(lihat Thomas, 2004:10).
Relasi kuasa para pihak sehubungan dengan adanya
strategi pertanahan, terdiri dari relasi antara
pihak-pihak, sebagai berikut: (1) Pemerintah Desa, sebagai pihak yang
menetapkan strategi pertanahan; (2) petani, sebagai pihak yang menjadi sasaran
strategi pertanahan; (3) kelompok tani, sebagai pihak yang memperjuangkan
kepentingan petani; (4) gabungan kelompok tani, sebagai pihak yang
memperjuangkan kepentingan kelompok tani.
Adanya relasi kuasa akibat strategi pertanahan berpotensi menimbulkan konflik. Namun demikian
diketahui, bahwa saat konflik telah berada dipuncak dalam bentuk kemacetan,
maka konflik akan menurun dan menuju tahap pengurangan (de-escalation), yang selanjutnya mengalami negosiasi dalam rangka
mencapai konsensus. Sumber konflik meliputi: Pertama, pemaknaan tanah oleh stakeholders,
yang meliputi perbedaan makna tanah menurut pemerintah desa, petani, kelompok
tani, dan gabungan kelompok tani. Kedua,
hak dan akses atas tanah, yang meliputi kepemilikan serta akses terhadap
keuntungan dan nilai-nilai pertanahan yang dianut. Ketiga, kontestasi antar aktor, yaitu: pemerintah desa, petani,
kelompok tani, dan gabungan kelompok tani
Dinamika kekuasaan
dan relasi kuasa (power relation)
merupakan faktor yang telah melipat-gandakan dan menjadi penyebab merebaknya
kemiskinan (poverty). Serangan
komprehensif terhadap kemiskinan dan ketidak-setaraan (inequality) berasal dari kekuasaan (power), termasuk peran konstruktif dan destruktif kekuasaan.
Pendekatan untuk mereduksi kemiskinan seringkali mengabaikan kebutuhan utama
masyarakat, serta meremehkan (underestimate)
dan mengabaikan relasi kuasa yang justru memelihara kemiskinan (Moncrieffe,
2004:7-11).
Angus Stewart
(dalam Agusta, 2008:266-267) membagi kekuasaan dalam dua bagian, yaitu: Pertama, kekuasaan yang hadir dalam
bentuk dominasi, yang dikenali sebagai kekuasaan meliputi (power over) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan jenis ini dipandang
sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan, melalui mobilisasi sumberdaya.
Selain itu, kekuasaan juga sejajar dengan otoritas, sehingga memiliki keresmian
dan legitimasi, untuk mendesakkan keinginan kepada orang lain; Kedua, kekuasaan yang hadir dalam
bentuk pemberdayaan, yang dikenali sebagai kekuasaan terhadap (power to) sesuatu atau seseorang. Kekuasaan
jenis ini dipandang sebagai wujud otonomi masyarakat, melalui proses
intersubyektif yang mampu menciptakan solidaritas bersama.
Keberadaan power over relation dan power to relation relevan dengan
definisi yang diungkapkan Robert A. Dahl (1957:201). Baginya kekuasaan (power) merupakan
terma (istilah) relasi antar orang (manusia), yang dinotasikan dalam simbol
sederhana. Ia (1957:202) juga mengungkapkan, bahwa para ilmuwan tidak hendak
memproduksi satu teori tentang kekuasaan, misal: Theory of Power, melainkan para ilmuwan cenderung memproduksi
beraneka-ragam teori, yang masing-masing dengan cakupan terbatas.
Kekuasaan (power) dapat bersifat konfliktual (conflictual) dan koersif (coercive), sehingga ia perlu dibangun
melalui konsensus (consensus) dan
legitimasi (legitimacy). Kekuasaan
bukanlah hal sederhana yang ada dengan sendirinya, melainkan sesuatu yang harus
dikultivasi (cultivated). Kekuasaan
tidak akan kehilangan kekuatannya, bila ia digunakan dengan memanfaatkan
berbagai taktik untuk mempengaruhi berbagai agenda. Kekuasaan merupakan wujud
adanya kewenangan yang legitimate (Moncrieffe, 2004:26-27).
Kekuatan kekuasaan
semakin nampak, ketika pandangan Marx, Weber, dan Gramsci diperhatikan dengan
sungguh-sungguh. Mereka bertiga adalah orang-orang yang menekuni teori
kekuasaan (power) pada masyarakat
berbasis kelas. Karl Marx (1818-1883) mengeksplorasi kekuasaan dalam relasinya
dengan buruh, kelas, ekonomi, dan sistem kapitalisme. Menurut Marx, di bawah
kapitalisme para pekerja dipaksa menjual tenaganya kepada kaum kapitalis, yang
akan menggunakan tenaga ini untuk mengakumulasi modal lebih banyak, untuk
meningkatkan kekuasaan kaum kapitalis atas para pekerja.
Sementara itu, Max
Weber (1864-1920) sepakat tentang perlunya distribusi kekuasaan dalam proses
yang berkaitan dengan buruh. Weber mengeksplorasi kekuasaan dalam terma
kewenangan (authority) dan manajemen
dalam birokrasi negara. Menurut Weber, kekuasaan adalah kesempatan yang
dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk menentukan sikapnya terhadap
suatu tindakan komunal, termasuk menentang orang lain yang berpartisipasi pada
tindakan komunal tersebut. Berbeda dengan Marx dan Weber, Antonio Gramschi
(1891-1937) mengajukan teori hegemoni sebagai perspektif, untuk menganalisis
struktur dan agensi. Teori hegemoni mendasarkan diri pada pandangan Kaum
Marxis, yang bergerak melintasi reduksionisme ekonomi (Murphy, 2007:12-19).
Kekuasaan berbasis
kelas tidaklah sepenuhnya benar, karena Foucault (dalam Sutrisno, 2005:154)
menjelaskan, bahwa kekuasaan bukan milik sispapun, kekuasaan ada di mana-mana,
dan kekuasaan adalah strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam
suatu ruang lingkup tertentu. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan
hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi
kekuasaan yang menandai subyek. Oleh karena itu, kekuasaan memproduksi
pengetahuan, dan pengetahuan menyediakan kekuasaan. Kekuasaan tidak selalu
bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga dapat melalui
normalisasi dan regulasi.
James C. Scott
(1981 dan 2000) menjelaskan, bahwa ketika para petani (peasant) mendapatkan ketidak-adilan, maka mereka tidak melakukan
perlawanan secara terbuka, melainkan melakukan resistensi. Strategi perlawanan
ini (resistensi) dimaksudkan untuk mempertahankan diri dengan cara-cara yang
lunak demi kelangsungan hidupnya. Perlawanan semacam ini oleh beberapa pihak
sering tidak diakui sebagai perlawanan, karena tindakannya tidak mengancam
pemilik kuasa (power). Bentuk
resistensi antara lain tdak ikut gotong royong, berbohong, ngemplang, dan
sabotase. Bentuk perlawanan tidak frontal ini dapat terjadi, karena adanya
moralitas petani yang lebih mementingkan keselamatan (keselarasan) dibanding
konflik.
Pendapat James C.
Scott dijernihkan oleh Samuel Popkin (1979), yang menyatakan, bahwa tindakan petani tidak
semata-mata karena moralitas petani, melainkan karena pertimbangan rasional.
Resistensi muncul dari kesadaran untuk memilih tindakan terbaik dan paling
menguntungkan bagi petani. Caranya antara lain dengan beralih ke pekerjaan lain
(non pertanian), cara ini lebih efisien daripada melakukan protes atau
menentang penguasa.
Hubungan para aktor dapat berwujud kerjasama, bahkan dapat menimbulkan
konflik, sehingga untuk memelihara relasi tersebut, diperlukan skema resolusi
konflik atau penyeimbangan kekuasaan antar aktor. Hubungan masing-masing aktor
dalam ranah pengelolaan sumberdaya alam juga ditentukan oleh ideologi
politik/kekuasaan dan orientasi ekonomi yang dianut aktor (Innah, 2012:98).
.jpg)